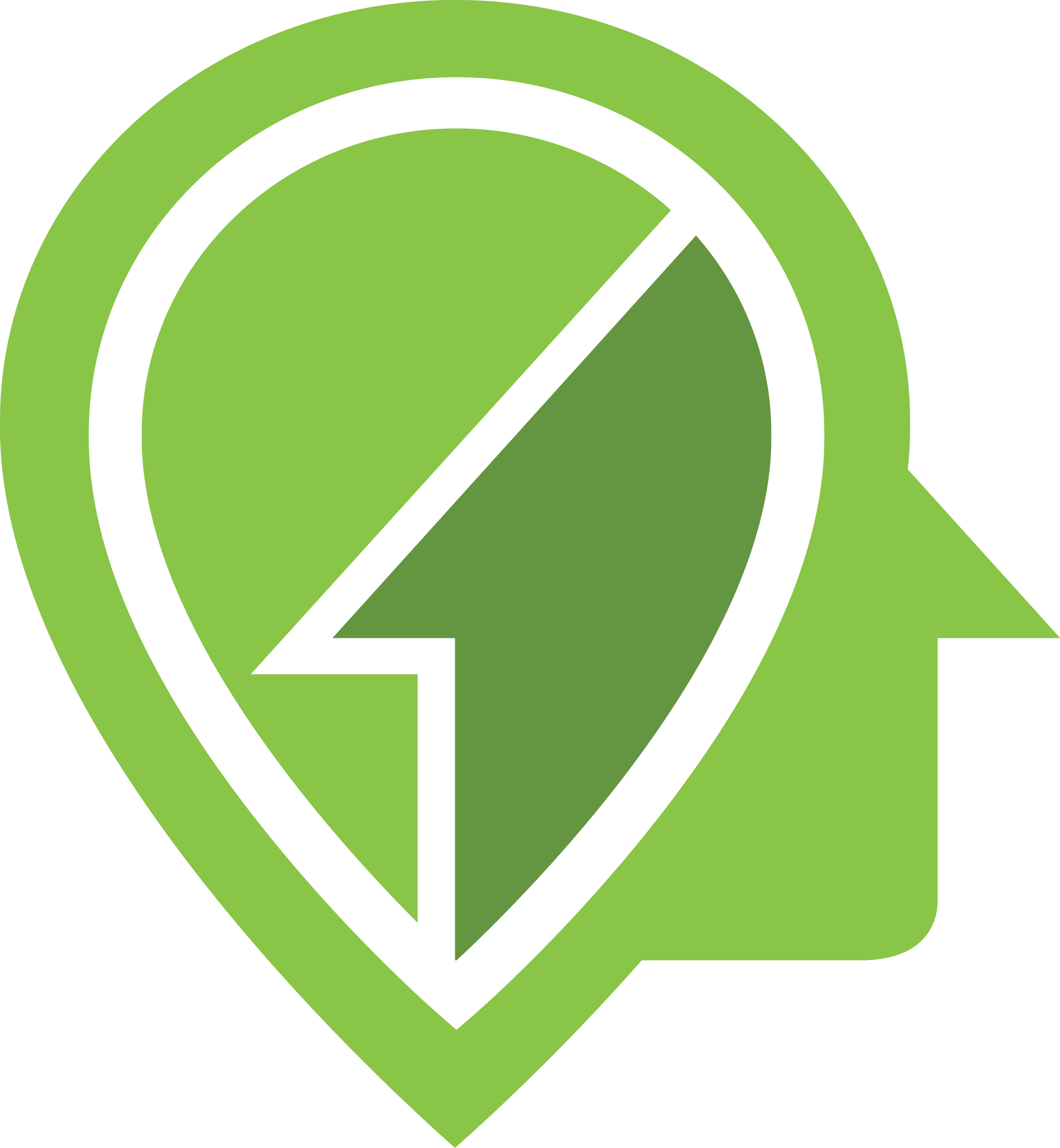Dualisme Tanah : Karakter dan Konteks
Masalah tanah selalunya berdimensi hukum formal. Hingga saat ini masih berlaku Hukum UU Pokok Agraria tahun 1960. Salah satu tujuan yang melatari UU Pokok agraria ini ialah untuk mengakhiri peraturan peninggalan kolonial Belanda yang diskriminatif, sekaligus mencari solusi bagi dualisme hukum antara peraturan kolonialisme Barat dengan hukum adat. Prinsip dasar UU Pokok Agraria bahwa negara menguasai tanah, dan semua tanah pada akhirnya harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Kusno, 2012). Hal ini menggaris bawahi bahwa BPN merupakan satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan memberikan status formal sebuah tanah.
Meski UU Pokok Agraria sudah lama diberlakukan, namun sampai saat ini dualisme tanah masih menjadi masalah mendasar. Adanya dualisme ini tentu berdampak pada kepastian hukum dan juga kepastian berusaha. Tidak saja terkait pembangunan properti, namun juga infrastruktur, perkebunan, kehutanan dan sebagainya. Termasuk tanah yang dipergunakan untuk ruang sosial dan kepentingan kemasyarakatan. Di sisi lain, kesimpangsiuran status tanah pada titik tertentu juga dapat memicu kerentanan dan konflik sosial.
Yang terjadi sekarang ini, pengertian dari dualisme tanah ini merujuk pada kondisi formal dan informal dari tanah di Indonesia. Pertama, dualisme formal dan informal mengacu pada perbedaan antara tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang belum terdaftar pada BPN. Tanah yang belum terdaftar inilah yang kemudian disebut tanah informal. Dengan demikian pada 1990an, sebagian besar lahan di kota masih berstatus ‘informal’. Pada saat itu diestimasi 70% luas tanah masih terkategori informal (Kusno, 2012). Angka yang sebenarnya cukup tinggi, namun ini memang lazim dijumpai di banyak negara berkembang. Berbeda dengan negara maju – Jepang misalnya, yang telah selesai dengan reforma agrarianya di tahun 1950an.
(Baca juga : Mencari Perumahan Syariah? Berikut Ini Ciri Cirinya)
Pengertian kedua, tanah berstatus informal (yang belum tercatat di BPN) itu sebenarnya terdaftar di kelurahan, dalam bentuk dokumen transaksi, surat – surat dan pembayaran administrasi yang disaksikan pejabat kelurahan. Jadi pembeli tanah informal itu berhak untuk tinggal di tanah tersebut, meskipun di mata BPN tanahnya masih diangap tidak sah dan belum terdaftar. Maka, perbedaan antara tanah ‘formal’ dan tanah ‘informal’ ada pada terdaftar tidaknya tanah tersebut di BPN (Kusno, 2012)
Jadi perlu dipahami, tanah informal – yang diperkirakan mencapai 70% dari luas total tanah itu – berarti tidak terdaftar di BPN. Dengan demikian, sebagian besar kampung – kampung di Jakarta masuk dalam kategori ini. Pada kenyataannya hanya 25-30 persen tanah di Jakarta yang berkategori ‘formal’ yakni terdaftar di BPN. Yang artinya juga tanah tersebut telah dipakai oleh pemerintah atau berada di bawah kekuasaan pasar properti real estate (Kusno, 2012).
[media-credit name=”admin/public_html/media” align=”none” width=”300″] [/media-credit]
[/media-credit]
Hal ini mengkonfirmasi pandangan Hardoy dan Satterthwaite, bahwa di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia, sistem pencatatan (registrasi) tanah hanya mencakup sebagian dari area perkotaan dan seringkali model nya pun usang. Sistem pencatatan tanah yang lengkap dan mutakhir bisa banyak membantu proses jual beli tanah secara legal dengan lebih cepat juga dan biaya terjangkau. Dengan mempermudah prosedur dan mempercepat proses untuk menyetujui permohonan pemilik tanah swasta untuk membagi – bagi kavling tanahnya untuk bisa dijual, bisa juga mengurangi biaya legalitas kavling dan mungkin juga membantu pemukim informal area perkotaan untuk memiliki tanah di pasar legal. Dengan demikian diharapkan bisa memperluas pasar keuangan perumahan, karena pribadi yang bisa menunjukkan kepemilikannya atau hak gunanya dengan dokumen legal bisa digunakan sebagai agunan dalam memperoleh pinjaman finansial. Ini pada akhirnya bisa membuat pembiayaan rumah jadi lebih murah (Hardoy & Satterthwaite, 1989).
(Baca juga : Memaknai Ruang Kota)
Lebih jauh tentang karakter dualisme tanah : formal dan informal. Bahwa sejatinya dualisme ini tidak berupa hitam putih. Bukan berupa dua buah kutub yang beseberangan, melainkan lebih mirip spektrum yang amat dinamis: sebuah gradasi. Sebuah persil tanah tidak bisa dianggap seratus persen formal, begitupun sebaliknya seratus persen informal. Tanah yang tidak bersertifikat BPN , karenanya informal , namun ternyata digunakan sebagai bangunan mess hunian aparatur negara misalnya. Tentu tidak sepenuhnya informal. Begitu juga tanah yang dikategorikan sebagai informal, namun kenyataannya ada keluar tagihan pajak kelurahan atau retribusi panen pertanian dari pemerintah desa misalnya, juga tidak bisa dianggap 100 persen informal. Yang saat ini berstatus informal pun bisa ditransformasi menjadi formal. Hanya saja cepat ataupun lambat prosesnya tergantung pada kapasitas kelembagaan , desakan pasar maupun tuntutan masyarakat setempat.
Respons Pasar Real Estate
Apa kemudian konsekuensinya? Pemisahan lahan berstatus ‘formal’ dan informal ini kemudian diperkuat oleh pasar formal (yang diasosiasikan dengan real estate) dan pasar informal. Meskipun demikian pemisahan ini tidak bersifat statis. Michael Leaf pernah menulis tentang sistem pertanahan di Indonesia bahwa: tanah informal yang hanya terdaftar di kelurahan itu bisa dianggap sebagai tanah transisional (peralihan), sebab ia bisa berubah status menjadi sepenuhnya legal di pasar formal, apabila telah di legalkan oleh BPN, yang mana seringkali oleh proses pengajuan dari pengembang (Kusno, 2012).
Dari sinilah mengapa ini terkait dengan pola kerja pengembang dan konsultan real estatenya. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengakomodasi kondisi dualisme tanah ini. Pengembang yang telah mapan juga menggunakan jaringan informan yang kuat di lapangan. Sebagaimana Simone berpandangan bahwa governance yang sebenarnya di kota Jakarta telah lama bergantung pada manajemen berpola subcontracting dengan berbagai macam otoritas, baik formal maupun informal (Simone, 2014). Perusahaan konsultan properti dan pengembang sebenarnya bisa dianggap sebagai pelaku di luar lokalitas yang ada, saat sebagaian besar tanah yang ada, belum terdaftar di BPN. Namun di lapangan, pemilik tanah beranggapan memiliki hak legal untuk mendiami berdasar klaim kepemilikan tanah yang mana merupakan hasil mediasi melalui kelurahan sebagai kantor administrasi lokal. Namun bagaimanapun proses klaim tanah ini rumit. Saat kelurahan melakukan mediasi terhadap klaim-klaim kepemilikan tanah, mereka biasanya mengandalkan hubungan personal dan ‘sejarah’ tempat tersebut dalam kerangka waktu tertentu. Kondisi ini barangkali tampak buram dan abu- abu bagi pihak luar, terutama saat sengketa yang kompleks terus terjadi turun temurun. Atau ditengah banyaknya klaim palsu yang masuk menambah rumit proses ini (Simone, 2014 dalam (Wade, 2019)
Dampak Formalisasi Tanah terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Terkait dengan proses sertifikasi yang sempat marak dilakukan. Sertifikasi pada umumnya disambut baik oleh masyarakat, kecuali masyarakat miskin dan tinggal secara ilegal di tanah negara. Untuk golongan yang lebih mampu dan memiliki lahan informal (artinya, hanya terdaftar di kelurahan) , upgrade berupa sertifikasi dari BPN memperkokoh status dan identitas “kelas menengah” mereka.
Sebaliknya, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), model hitam putih informal –formal tidak memberi banyak pilihan bagi mereka , terkecuali mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memformalkankannya. Untuk bisa sesuai dengan standar tata ruang yang benar. Belum lagi perjalanan yang mesti dilakukan, bolak – balik ke kantor pertanahan, menunggu antrian dokumen yang seringkali tidak jelas batas waktunya. Sehingga banyak orang habis waktu yang sebenarnya bisa digunakan bekerja.
(Baca juga : Penting! Inilah Hubungan Covid19 dan Lingkungan Rumah yang Sehat)
Karena itu, yang perlu dicermati ialah jebakan untuk tidak begitu saja ‘memformalkan’ semua tanah yang belum terdaftar. Jika ini dilakukan terlalu cepat, tidak menggunakan pendekatan empati, dan tanpa pertimbangan kondisi dan penghidupan keluarga miskin, akan semakin membebani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Di mata pemerintah proses sertifikasi adalah juga proses inventarisasi lahan yang pada ujungnya membuat mereka – yang secara ilegal tinggal di ‘lahan terlantar’ – semakin ‘tergencet’. Jika tidak cermat dilakukan, proses setifikasi bisa melahirkan kebijakan penggusuran (Kusno, 2012). Sertifikasi menjadi semacam lampu hijau yang memuluskan jalan bagi tindakan penggusuran. Memaksa mereka keluar dari tanah tersebut . Paling tidak ikut mendorong penggusuran sukarela dan akan semakin meminggirkan mereka. Konsekuensinya bisa menimbulkan kompleksitas sosial bahkan gejolak yang beresiko bagi ekonomi dan kemashlahatan yang lebih luas.
- Romi Romadhoni, MDP
He is an urban planner and sociopreneur, and can be reached at m.romadhoni@gmail.com and twitter : @romi_mr
Referensi
Hardoy, J., & Satterthwaite, D. (1989). Squatter Citizen : Life in the Urban Third World. London: Earthscan Publications Ltd.
Kusno, A. (2012). Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta. Jakarta: Penerbit Ombak.
Wade, M. (2019). Island City: Urban Development, Planning, and Real Estate in Jakarta . the University of California, Berkeley, Global Metropolitan Studies in the Graduate Division . Berkeley, CA: the University of California, Berkeley.